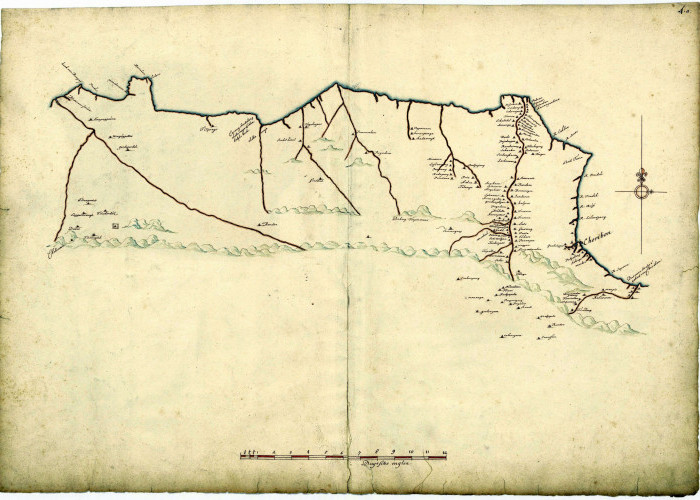Peran Vital Ponpes dalam Membangun Persatuan Bangsa

Pernahkah ada Indonesia, jika tidak pernah ada pesantren? Pertanyaan dimaksud, sepintas seperti berlebihan dan cenderung mengada-ada. Tetapi kalau berkaca dari kacamata sejarah, pertanyaan di atas, sebenarnya memiliki relevansi dengan kenyataan bahwa, nation state bernama Indonesia, justru dipersatukan oleh apa yang disebut dengan kaum agamawan (baca Islam) yang dalam banyak kasus memperoleh pendidikan di pesantren. Narasi di atas, dapat dikaji misalnya dari apa yang pernah dinyatakan Nurcholish Madjid (1991) yang menyebut bahwa, sekadar bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia, adalah berkat para ulama. Sebelumnya, bahasa Melayu hanya merupakan alat komunikasi lokal di sebuah tempat yang sangat kecil di suatu semenanjung bernama Melayu. Bahasa ini, berubah menjadi bahasa komunikasi yang sangat populer, berkat jerih payah para ulama dan intelektual Muslim ketika mereka melakukan aktivitas dagang dan dakwah Islamiyah ke seantero Nusantara. Bahasa Melayu kemudian berkembang menjadi bahasa yang mudah dipahami, seluruh warga masyarakat Nusantara. Nurcholish Madjid menyatakan pilihan para intelektual Muslim dalam menggunakan Bahasa Melayu ketika melakukan komunikasi bisnis dan dakwah ke seluruh wilayah Nusantara, karena bahasa ini secara teologis berbeda dengan bahasa lain di Nusantara. Sebut misalnya, mengapa mereka tidak menggunakan Bahasa Jawa atau Bahasa Sunda. Padahal kedua bahasa ini, dipakai masyarakat mayoritas yang mendiami linguapranca yang ketika merdeka disebut Indonesia. Dalam analisa Nurcholish Madjid (1991), pilihan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi, karena bahasa ini dianggap memiliki budaya yang sangat dekat dengan budaya dan bahkan teologi Islam. Bahasa ini mengajarkan kesejajaran dan kesamaan kedudukan (equal and equity) manusia antara yang satu dengan yang lain. Prinsip dasar bahasa Melayu yang demikian, dianggap dekat dengan jiwa ajaran Islam, yang justru menempatkan kesamaan kedudukan dan kesejajaran termasuk dalam soal kehormatan di antara sesama umat manusia. Jadi, ketika para pemuda daerah se-Nusantara mendeklarasikan Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) yang dalam salah satu butirnya menyebut, satu bahasa yakni Bahasa Indonesia, secara historis, sejatinya telah diprakarsai komunitas Muslim, yang “tidak terdidik” dalam pendidikan persekolahan Belanda dan Jepang selama kurun waktu lebih dari 3,5 abad. Mereka secara umum, justru memperoleh pendidikan, di institusi-institusi pendidikan informal, yakni pondok pesantren. Dilihat dari perspektif ini saja, pesantren dalam membangun bangsa Indonesia, tampak dengan jelas. PERSATUAN DAN KESATUAN ADALAH JIWA PESANTREN Dengan narasi di atas, maka, budaya equal and equity, secara implisit jika membaca tulisan Zamakhsyari Dhofier (1982), sesungguhnya adalah budaya pesantren. Institusi pendidikan pesantrenlah, yang tetap mewadahi dan mengakomodasi seluruh tatanan sosial masyarakat yang tidak mungkin baik secara sosiologis, antropologis dan bahkan politis, mampu diwadahi pendidikan sekolah, yang waktu itu hanya milik bangsa penjajah. Paling jauh, lembaga pendidikan Belanda dan Jepang hanya mewadahi kelompok asing (seperti Tiongkok dan Arab) dan aristokrat tertentu, yang secara politis memang dipelihara penjajah. Kaum pribumi tetap dibiarkan menjadi inlander. Hal ini persis seperti apa yang disarankan Machiavelli, yang menasihati para pemimpin negara untuk membiarkan penduduknya tetap bodoh agar mudah “ditipu” oleh kepentingan penguasa. Kaum pribumi sebagai lapis terbawah dari tatanan masyarakat dan bangsa Nusantara waktu itu, tidak mungkin memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan formal. Inilah yang menyebabkan, mengapa dalam banyak kasus, pendidikan pesantren tetap memiliki keandalannya tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan apapun yang terjadi di lingkungan sosial kemasyarakatan Indonesia, vitalitas pesantren sebagai kekuatan sosial, kultural, keagamaan dan tetap aktif membangun kebudayaan Indonesia modern, tetaplah terasa. Jadi, dengan kata lain, sekalipun pada saat ini, masyarakat Indonesia yang sudah menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka, dan setiap warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama antara yang satu dengan yang lain untuk mengikuti pendidikan di lembaga formal (baca sekolah/madrasah), pesantren tetaplah ajeg sebagai lembaga pendidikan berbasis kerakyatan, dengan konsepnya yang utuh pada suatu adagium: “hubb al wathan min al iman”. Narasi dan diksi di atas, jika dikaitkan dengan konteks sosial politik dan bahkan ideologi bangsa, pesantren tetaplah memiliki elan vital yang cukup serius. Sebut misalnya, mengapa dalam priamble UUD 1945, di situ sangat terasa bagaimana komunitas Muslim mempengaruhi suatu landasan hukum dan UU yang berlaku di Indonesia. Misalnya, ketika kita bertemu dengan kalimat: “.... Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa .... “ dalam UUD 1945 dimaksud, semua kata tersebut, menunjukkan wataknya bahwa Islam telah menjadi pilar bernegara dalam konteks Indonesia. Dan karena Islam dipopulerkan dan ditransmisikan (suatu istilah Azyumardi Azra, 2001) melalui pesantren, maka, kedudukan dan fungsi pesantren dalam konteks kebangsaan tadi, tentu saja sangat vital. Mengabaikan peran lembaga ini dalam konteks membangun budaya bangsa tadi, sejajar atau semakna dengan pengaburan terhadap dimensi sejarah kebangsaan dan keindonesiaan itu sendiri. Belum lagi kalau berbicara mengenai pengakuan atas Pancasila sebagai dasar negara. Diketahui bahwa dari sembilan tokoh nasional yang menjadi perumus Pancasila tadi, delapan di antaranya adalah kaum santri. Penghapusan tujuh kata, yakni: “.... dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang tertuang dalam sila pertama pada Pancasila, yang dikenal dengan Jakarta Carter, adalah sikap terbuka kaum santri terhadap, bukan saja nasionalisme Indonesia, tetapi, juga pengakuan multi religi yang hidup di tengah bangsa yang multi cultural. Akhirnya, harus penulis sampaikan bahwa, dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia, peran pesantren bukanlah asal-asalan dan gagah-gagahan. Tetapi nyata dalam membangun bangsa yang plural. Karena itu, juga patut disebut bahwa, jika ada yang menyatakan bahwa pesantren menjadi institusi anti toleran, dan bahkan dianggap radikalis, maka, tuduhan-tuduhan seperti itu, bukan hanya melecehkan peran pesantren, tetapi, juga sebenarnya melemahkan bangsa itu sendiri.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: